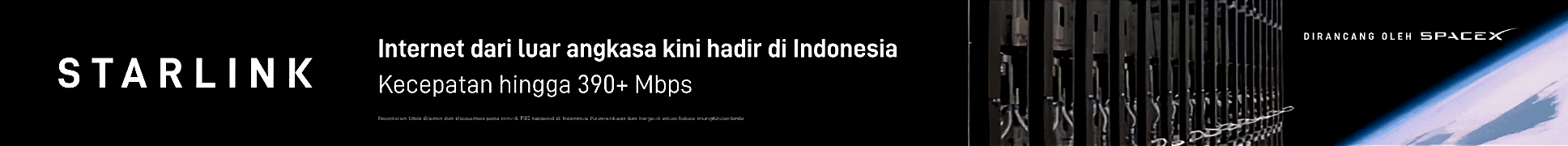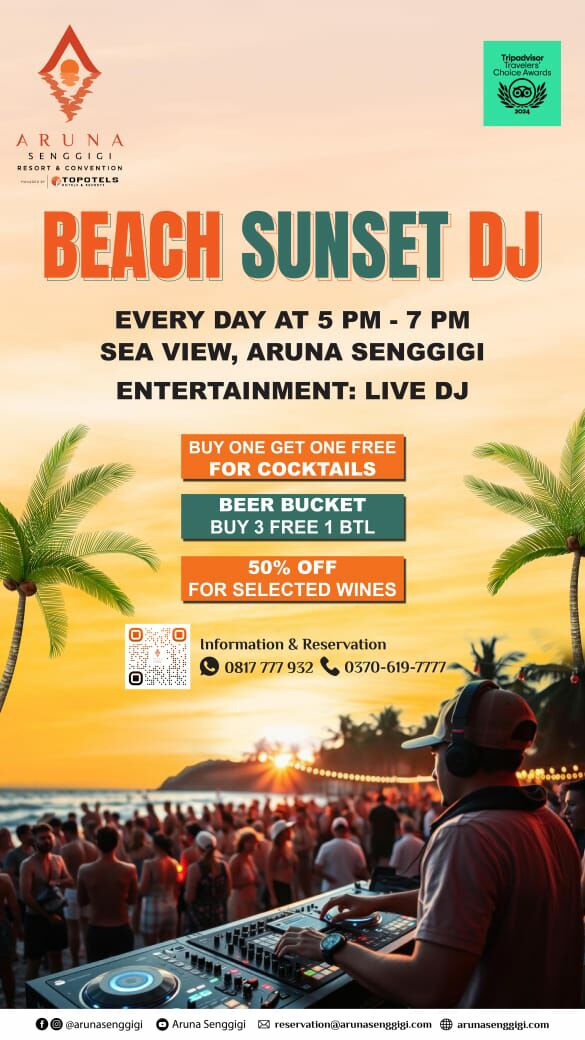Kontroversi materi Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono membuka satu soal mendasar yang kerap luput dibahas: bukan apakah komedi boleh mengkritik kekuasaan, melainkan seberapa malas kritik itu disusun.
Lelucon tentang mata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut “mengantuk” mungkin terdengar sepele di panggung, tetapi problematik ketika ditarik ke ruang publik yang lebih luas.
dr. Tompi mengoreksi bukan dari sudut moral semata, melainkan dari ranah ilmu. Ia menegaskan bahwa apa yang disebut “mata mengantuk” secara medis dikenal sebagai ptosis, kondisi anatomis yang bisa bawaan, fungsional, atau medis.
Fakta ini penting karena membongkar satu kelemahan mendasar: lelucon itu tidak menyerang kekuasaan, tidak menguliti kebijakan, dan tidak membongkar relasi kuasa ia hanya menyentil tubuh.
Di sinilah kritik menjadi relevan. Satire politik secara historis lahir untuk menampar ide, bukan menertawakan kondisi biologis.
Ketika humor turun kelas menjadi ejekan fisik, ia kehilangan fungsi kritisnya dan berubah menjadi sekadar hiburan instan. Lucu, mungkin. Tajam, tidak.
Pembelaan klasik bahwa “ini kan cuma komedi” justru problematik. Komedi bukan ruang hampa nilai. Ia membentuk persepsi, membangun normalisasi, dan dalam konteks politik, ikut mempengaruhi cara publik menilai pemimpin.
Menertawakan fisik sesuatu yang tidak bisa dipilih adalah kritik termurah dalam katalog kritik kekuasaan.
Keprihatinan Ina Liem menambah dimensi lain: tanggung jawab kultural. Sebagai pendidik, ia melihat materi seperti ini bukan sekadar soal selera humor, melainkan soal teladan berpikir.
Ketika komedi politik lebih sibuk mengulik tubuh ketimbang kebijakan, publik diajak tertawa tanpa diajak berpikir. Ini berbahaya dalam iklim demokrasi yang sudah rentan terhadap simplifikasi dan polarisasi.
Perlu ditegaskan: kritik terhadap materi ini bukan berarti membela Gibran sebagai pejabat. Justru sebaliknya, Gibran memiliki banyak ruang kritik yang sah rekam kebijakan, etika kekuasaan, proses politik yang mengantarkannya ke jabatan, hingga implikasi demokratisnya.
Mengabaikan semua itu dan memilih fisik sebagai bahan lelucon adalah pemborosan peluang kritik.
Sikap Pandji yang menerima masukan patut diapresiasi. Itu menunjukkan ruang dialog masih terbuka. Namun penerimaan saja tidak cukup jika tidak diikuti refleksi.
Komedi politik yang matang seharusnya naik kelas: dari mengejek tampilan menuju membedah struktur, dari punchline instan menuju kritik yang menggigit.
Pada akhirnya, polemik ini bukan soal selera humor, melainkan standar nalar publik.
Demokrasi tidak anti-tawa, tetapi ia alergi pada kritik yang malas. Ketika fisik dijadikan senjata, itu tanda argumen kehabisan peluru. Dan saat kritik berhenti di tubuh, kekuasaan justru lolos tanpa disentuh.
Di titik inilah diskusi Tompi, Ina Liem, dan respons Pandji menjadi relevan: humor boleh bebas, tetapi martabat manusia tidak semestinya menjadi punchline. Kritik yang kuat lahir dari ide, bukan dari kelopak mata. ***
Penulis : Weid Must
Editor : Suluh NTB Editor