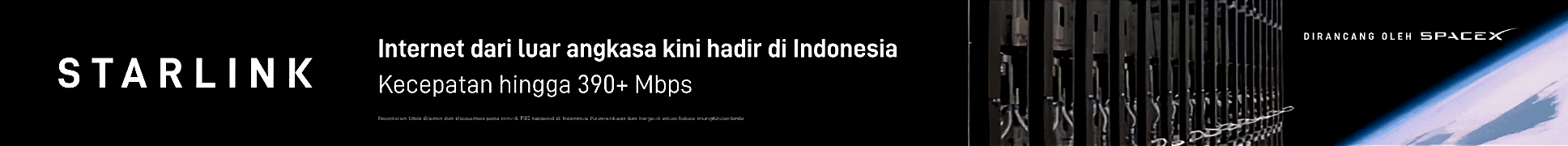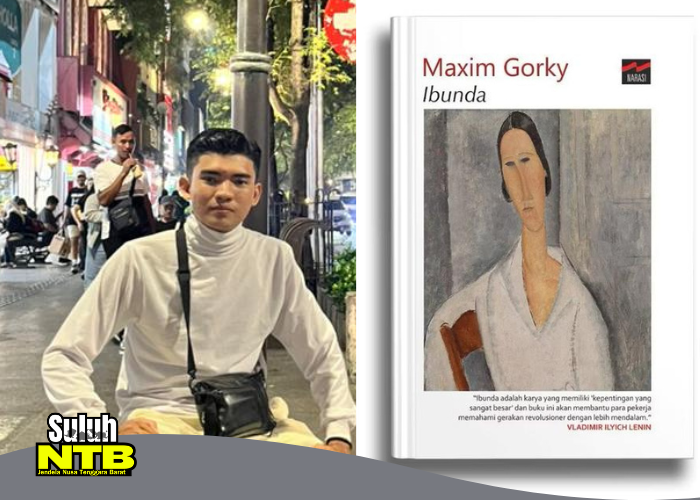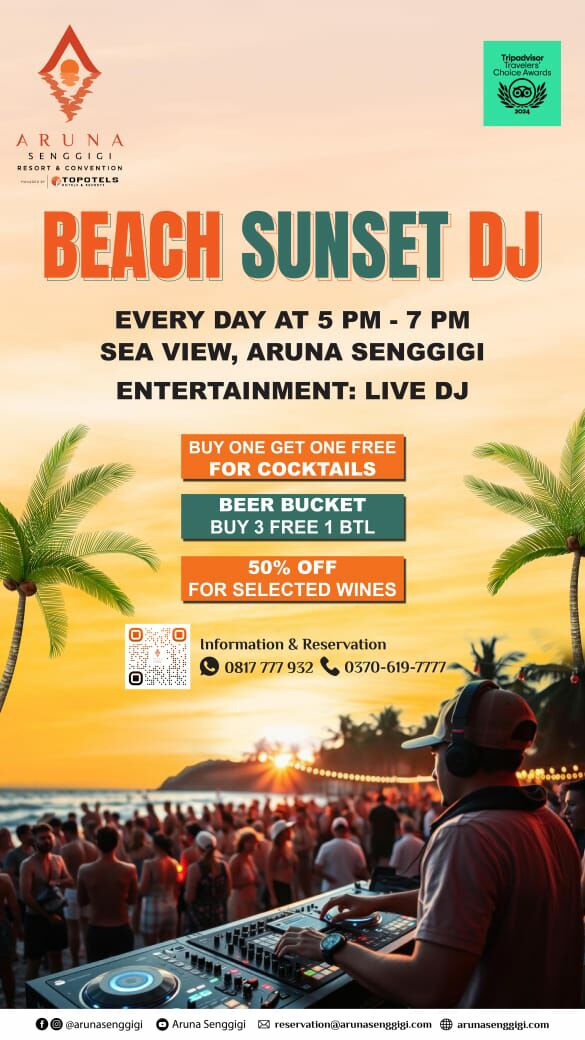Penulis : Muhamad Dicky Subagia (Direktur Umum Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur)
Hari Ibu kerap diperingati sebagai perayaan kasih dan pengorbanan perempuan dalam ruang domestik. Narasi yang dominan menempatkan ibu sebagai simbol kelembutan, kesabaran, dan ketulusan tanpa syarat.
Namun, perayaan semacam ini sering kali terjebak dalam romantisasi, bahkan depolitisasi, peran ibu. Ia mengaburkan fakta bahwa pengalaman keibuan tidak pernah netral, melainkan selalu berada dalam pusaran relasi kuasa, struktur kelas, dan kondisi material yang melingkupinya.
Dalam konteks ini, novel Ibunda (The Mother, 1906) karya Maxim Gorky menjadi teks penting untuk membaca ulang makna Hari Ibu secara kritis dan ilmiah.
Maxim Gorky, sebagai sastrawan realisme sosialis Rusia, menghadirkan figur ibu bukan sebagai ikon sentimental, melainkan sebagai subjek sejarah yang mengalami transformasi kesadaran.
Tokoh Pelageya Nilovna Vlasova, seorang ibu dari kelas pekerja digambarkan hidup dalam ketakutan, kemiskinan, dan kekerasan domestik. Ia adalah potret perempuan proletar yang lama diposisikan sebagai korban pasif dari sistem kapitalisme dan patriarki. Namun, justru dari posisi marjinal inilah Gorky membangun narasi keibuan yang politis.
Untuk membongkar reduksi makna tersebut, karya Ibunda (1906) oleh Maxim Gorky menawarkan lensa kritis yang tajam. Novel ini tidak hanya berbicara tentang seorang ibu, tetapi tentang proses transformasi kesadaran keibuan dalam pusaran perjuangan kelas dan penindasan struktural.
Melalui tokoh Pelageya Nilovna Vlasova, Gorky menghadirkan figur ibu yang bergerak dari kepasrahan menuju keberanian politik, dari ibu rumah tangga menjadi subjek sejarah.
Ibu dalam Struktur Penindasan: Dari Ketakutan ke Kesadaran
Pada bagian awal Ibunda, Pelageya digambarkan sebagai perempuan yang hidup dalam ketakutan yaitu takut pada suami yang kasar, takut pada negara yang represif, dan takut pada perubahan.
Ia adalah representasi perempuan kelas pekerja dalam sistem kapitalisme industrial Rusia pada awal abad ke-20, ia tidak berdaya, terpinggirkan, dan dibungkam oleh struktur patriarki yang dilegitimasi oleh kekuasaan negara.
Secara sosiologis, kondisi Pelageya mencerminkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai symbolic violence, yakni penindasan yang diterima sebagai kodrat.
Ibu diajarkan untuk patuh, diam, dan mengabdi, bukan karena itu pilihan bebas, melainkan karena struktur sosial tidak menyediakan alternatif yang setara. Dalam konteks ini, Hari Ibu yang hanya memuja ketulusan pengorbanan justru mengafirmasi kekerasan simbolik tersebut.
Transformasi Pelageya dimulai melalui relasinya dengan sang anak, Pavel Vlasov, seorang buruh muda yang terlibat dalam gerakan sosialis.
Awalnya, Pelageya hanya berperan sebagai ibu yang cemas dan takut akan risiko yang dihadapi anaknya. Namun, seiring waktu, ia tidak hanya memahami ide-ide perjuangan kelas yang dibawa Pavel, tetapi juga menginternalisasinya.

Kesadaran Pelageya bergerak dari ketakutan individual menuju keberanian kolektif. Ia tidak lagi sekadar melindungi anaknya secara biologis, melainkan ikut melindungi gagasan tentang keadilan sosial.
Keibuan sebagai Kesadaran Politik
Puncak penting dalam Ibunda adalah ketika Pelageya tidak lagi sekadar ibu dari Pavel, melainkan menjadi bagian dari gerakan itu sendiri.
Ia menyelundupkan pamflet, menghadiri pertemuan, dan berani melawan aparat negara. Keibuan dalam novel ini tidak direduksi sebagai fungsi biologis, melainkan diredefinisi sebagai energi moral dan politik yang berpihak pada keadilan.
Dari perspektif teori feminisme Marxis, Pelageya merepresentasikan kesadaran kelas perempuan yang bangkit dari ranah domestik menuju ranah publik.
Gorky menunjukkan bahwa pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pembebasan kelas tertindas secara keseluruhan. Ibu bukan hanya tiang keluarga, tetapi juga potensi aktor perubahan sosial.
Dalam perspektif sosiologi kritis, Ibunda menegaskan bahwa keibuan adalah bagian dari proses reproduksi sosial. Ibu tidak hanya mereproduksi tenaga kerja secara biologis, tetapi juga mereproduksi kesadaran, ideologi, dan nilai-nilai sosial.
Pelageya menjadi medium penyebaran ide perjuangan kelas, menyebarkan selebaran, menghadiri pertemuan rahasia, dan akhirnya berdiri di ruang publik sebagai subjek politik. Keibuan, dalam bingkai ini, tidak lagi dibatasi oleh tembok rumah, melainkan menembus ruang sosial yang lebih luas.
Lebih jauh, Gorky secara implisit mengkritik sistem yang memaksa ibu memilih antara keselamatan keluarga dan keberpihakan pada keadilan sosial.
Pelageya sadar bahwa keterlibatannya dalam perjuangan membawa risiko besar, namun ia juga memahami bahwa diam berarti turut melanggengkan ketidakadilan yang akan terus menghantui generasi berikutnya.
Inilah dilema struktural yang jarang dibicarakan dalam perayaan Hari Ibu yang serba romantik bahwa banyak ibu, terutama dari kelas pekerja, menjalani keibuan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, represi politik, dan minimnya perlindungan sosial.
Jika dikaitkan dengan konteks Hari Ibu hari ini, Ibunda mengajarkan bahwa memuliakan ibu tidak bisa dilepaskan dari pembacaan struktural atas realitas sosial.
Pujian terhadap pengorbanan ibu menjadi problematik ketika negara dan masyarakat gagal menyediakan sistem perlindungan yang adil, mulai dari akses kesehatan, jaminan kerja, hingga perlindungan dari kekerasan domestik. Ibu dipuji sebagai pahlawan, tetapi dibiarkan berjuang sendirian dalam sistem yang timpang.
Di sinilah Hari Ibu seharusnya dimaknai ulang. Bukan sekadar perayaan peran domestik, melainkan pengakuan atas perjuangan ibu sebagai subjek sosial politik, ibu yang bekerja tanpa jaminan, ibu yang melawan kemiskinan struktural, ibu yang menghadapi kekerasan, serta ibu yang berdiri di garis depan perubahan dan sering kali tanpa pengakuan negara.
Hari Ibu sebagai Arena Kritik Sosial
Dalam konteks Indonesia, refleksi Gorky menjadi sangat relevan. Banyak ibu terjebak dalam beban ganda yaitu kerja reproduktif yang tak dibayar di rumah dan kerja produktif di sektor informal yang minim perlindungan.
Negara sering merayakan ibu dalam retorika moral, tetapi abai dalam kebijakan tentang minimnya perlindungan maternitas, tingginya angka kematian ibu, serta lemahnya jaminan sosial bagi perempuan pekerja.
Dalam konteks Indonesia, pembacaan Ibunda menjadi relevan ketika kita melihat kondisi ibu buruh, ibu tani, ibu nelayan, dan ibu rumah tangga miskin kota yang menopang ekonomi keluarga melalui kerja ganda serta kerja domestik yang tak dibayar dan kerja produktif yang sering kali eksploitatif.
Hari Ibu, jika tidak dibaca secara kritis, berpotensi menjadi ritual simbolik yang justru menutupi problem struktural tersebut.
Jika ditarik ke konteks kontemporer, pembacaan Ibunda menegaskan bahwa penghormatan terhadap ibu tidak cukup diwujudkan dalam simbol perayaan tahunan.
Ia harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan sistem sosial yang memungkinkan ibu menjadi subjek yang merdeka dalam artian bebas dari kekerasan, dari kemiskinan struktural, serta memiliki akses setara terhadap pendidikan, ekonomi, dan ruang politik.
Membaca Ibunda pada Hari Ibu berarti menggeser fokus dari ucapan terima kasih menuju tanggung jawab struktural.
Menghormati ibu bukan hanya dengan bunga dan kata manis, tetapi dengan keberpihakan kebijakan, keadilan ekonomi, dan pembongkaran relasi kuasa yang menindas.
Gorky melalui karyanya yang berjudul Ibunda menawarkan narasi alternatif yaitu ibu sebagai aktor perubahan sosial. Pelageya bukan tokoh heroik dalam arti konvensional, ia tidak bebas dari rasa takut.
Namun justru di sanalah kekuatan dan keberaniannya yang lahir dari kesadaran, bukan dari romantisasi. Ia menunjukkan bahwa keibuan memiliki potensi emansipatoris ketika disertai kesadaran kelas dan keberpihakan pada keadilan.
Oleh karena itu, Hari Ibu seharusnya menjadi ruang refleksi kritis, bukan sekadar perayaan simbolik. Membaca Ibunda mengingatkan kita bahwa ibu bukan hanya objek penghormatan, tetapi subjek sejarah yang berhak atas kebebasan, keamanan, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik.
Memuliakan ibu berarti memperjuangkan sistem yang memanusiakan perempuan, bukan hanya memuji pengorbanannya.
Pada akhirnya, Hari Ibu menemukan makna terdalamnya bukan dalam bunga dan kata-kata manis, melainkan dalam komitmen kolektif untuk membangun struktur sosial yang adil.
Seperti Pelageya dalam Ibunda, ibu adalah penjaga kehidupan sekaligus penjaga kesadaran. Dan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang pandai memuji ibu, melainkan bangsa yang berani membebaskannya.
Hari Ibu bukan hanya tentang kasih yang lembut, tetapi tentang kesadaran dan keberanian. Seperti Pelageya dalam Ibunda karya Maxim Gorky, ibu adalah subjek sejarah dari ruang domestik yang mampu melahirkan kesadaran sosial, keberanian melawan ketidakadilan, dan harapan akan dunia yang lebih manusiawi.
Melalui Ibunda, Maxim Gorky mengajarkan bahwa keibuan bukanlah identitas pasif, melainkan proses dialektis yang dapat melahirkan kesadaran kritis dan keberanian politik.
Hari Ibu, dengan demikian, seharusnya menjadi momen refleksi kolektif, sejauh mana kita telah memanusiakan ibu, bukan hanya dalam simbol, tetapi dalam struktur kehidupan nyata.
Merayakan Hari Ibu secara kritis berarti menolak romantisisme kosong dan memilih keberpihakan. Sebab, seperti Pelageya Nilovna, ibu bukan sekadar yang melahirkan kehidupan, tetapi juga yang mampu melahirkan perubahan.
Penulis : Muhamad Dicky Subagia
Editor : Suluh NTB Editor